Sejarah Kecamatan Sanga Desa
 |
| Rumah Marga Sanga Desa wakap Peninggalan Depati Anang |
APERO
FUBLIC.-
Peristiwa pembentukan Marga Sanga Desa atau sekarang dikenal sekarang
dengan Kecamatan Sanga Desa memberikan informasi budaya. Bagaimana sosial
budaya masa lalu, bagaimana hubungan marga dengan sultan di Palembang,
bagaimana pembentukan pemerintahan marga-marga di Sumatera Selatan sebelumnya.
Pemerintahan Adat Tradisional Negara-Desa
Negara-Desa
istilah untuk menyebut pemerintahan adat yang memiliki kawasan wilayah seukuran
desa masa kita sekarang yang dipimpin seorang depati yang merdeka. Menurut W.
Marsden menginformasikan dari tahun 1883 gelar depati dipakai oleh pemimpin
dusun atau desa. (Arslan Islami: 2004).
Dalam
syair kisah pembentukan Marga Sanga Desa informasi dari Marsden terbukti. Kabar
negara-desa yang merdeka dan luasnya kekuasaan Sultan Palembang tergantung
pengakuan masyarakat uluan juga terbukti. Seberapa luas wilayah yang mengakui
maka seluas itu juga teritori kesultanan. Kalau wilayah tidak mengakui lagi
maka teritori juga berkurang. Yang tidak mengakui berarti merdeka.
Marga Sanga Desa
Marga
Sanga Desa merupakan nama pemerintahan lokal yang terdiri dari beberapa desa
yang bersatu, bersifat mandiri-semi merdeka. Wilayah ini mengurus rumah tangga
marga sendiri. Pemerintahan marga yang mandiri berakhir saat Kesultanan
Palembang dihapus Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1824.
Pemerintahan
marga yang mandiri, beransur-ansur menjadi bagian dari wilayah kabupaten atau
onderafdeling. Pemimpin dan perangkat mulai digaji kolonial, dan tidak lagi
mandiri-merdeka. Depati yang awalnya banding ke Palembang kalau ada masalah.
Sekarang bertanggung jawab pada Kontroleur (pejabat Belanda).
Pada
zaman kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem
marga masih dipakai sampai akhirnya dihapus zaman Orde Baru. Sejak saat itulah,
nama-nama marga diganti dengan istilah Kecamatan. Gelar Depati diganti dengan
Pak Camat. Seorang camat bukan asli dari wilayah marga, tapi berasal dari
berbagai wilayah dengan pendidikan negara. Itulah mengapa Camat tidak memiliki
fungsi apa-apa, selain kantor di kecamatan. Begitu juga Marga Sanga Desa
diganti menjadi Kecamatan Sanga Desa.
Sejarah Pembentukan Marga Sanga Desa
Pada
abad ke 18 Masehi kehidupan di Sumatera Selatan masih hidup sesuai kebudayaan
asli. Begitu juga di kawasan berdirinya Kecamatan Sanga Desa. Masyarakat di
sini hidup terpisah-pisah di pedalaman. Pemukiman terdiri dari
pemukiman-pemukiman rompok, talang dan dusun.
Rompok
pemukiman kecil yang terdiri dari beberapa pondok sederhana yang semi permanen.
Kadang rompok menjadi talang, dan lebih sering ditinggal dalam waktu beberapa
tahun. Rompok pemukiman untuk berladang berpindah. Ketika ladang sudah jauh
dari pemukiman utama (dusun) maka mereka membangun rompok.
Rompok
yang setrategis sering menjadi Talang. Talang pemukiman kecil yang dihuni
sekitar dua puluh sampai empat puluh keluarga atau lebih. Pengertian ini untuk
zaman yang lebih maju, kalau zaman sebelum era-Sriwijaya talang merupakan nama
pemukiman utama. Talang terdapat banyak kebun buah-buahan dan terletak
disekitar sungai yang dapat dijadikan untuk transportasi sekaligus untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Rompok dan Talang masih menginduk ke dusun yang
dipimpin depati.
Zaman
Kedatuan Sriwijaya berkembangnya istilah-istilah yang diambil dari bahasa
Sanskerta. Untuk membedakan pemukiman yang lebih ramai dalam administrasi
Sriwijaya, maka pemukiman yang ramai dinamai dengan Dusun. Kata dusun ini
merupakan serapan dari kata dalam bahasa Sanskerta, Desa.
Dalam
sistem pemerintahan adat Negara-Dusun atau Negara-Desa ini masih menggunakan
sistem kepuyangan. Dimana terdapat kelompok-kelompok keluarga besar atau tumang
(klan). Setiap klan memiliki talang dan rompok warga masing-masing. Mereka
menyatu dengan pemerintahan depati desa mereka. Walau mereka tinggal
terpencar-pencar di talang atau rompok di dalam hutan-hutan.
Pada
abad ke 18 masehi wilayah Marga Sanga Desa terbagi-bagi dalam wilayah
negara-desa seperti itu. Setiap kawasan ada depati yang berkuasa dan merdeka.
Tidak tunduk pada pemerintahan mana pun dan dimana pun. Wilayah negara-desa ini
luasnya sesuai wilayah ladang berpindah, rompok dan talang warganya.
Depati Samsudin Pendiri Marga Singa Desa
Depati
Samsudin atau Depati Uding adalah Depati dari Dusun Rengas Gemuruh. Adik
perempuannya bernama Dayang Turik. Dari namanya dia sudah jelas seorang Muslim.
Wilayah Dusun Rengas Gemuruh juga dinamakan, Kinyau. Menurut Odi Anang Kinyau
nama daerah dan Rengas Gemuruh ibu kotanya. Dusun Rengas Gemuruh merupakan
negara-desa yang merdeka tidak masuk dalam kesultanan Palembang. Sistem
pemerintahan adat yang terdiri dari dalam puluhan tumang, pimpinan Puyang Jurai
Tue.
Di
kawasan ini yang bakal dibentuk Pemerintahan Marga terdapat puluhan negara-desa
yang merdeka sama seperti Dusun Rengas Gemuruh. Setiap negara-desa memiliki
Depati masing-masing, wilayah dan rakyat masing-masing. Dengan banyaknya
kekuatan tentu berdampak pada stabilitas daerah. Tidak ada hukum tunggal yang
memberikan perlindungan. Sehingga hukum berjalan sendiri-sendiri, dan banyak
kekacauan.
Depati
Samsudin dikenal sebagai depati yang kejam, dan bengis. Sehingga dia ditakuti
oleh banyak orang. Banyak masyarakat yang tidak mau melewati kawasan Kinyau
karena takut. Membuat pedagangan dan komunikasi terputus. Para pedagang yang
akan ke hulu Musi melalui anak-anak sungai Musi seperti Sungai Punjung dan
lainnya, lalu masuk sungai Musi di bagian hulu Dusun Rengas Gemuruh atau
Kinyau.
Suatu
hari Dusun Rengas Gemuruh kedatangan pengembara bernama Limparan dari Basma
(Pasmah) dan dapat diterima dengan baik oleh Depati Samsudin. Limparan ini
orang misterius, namun berhasil mempengaruhi Depati Samsudin untuk membangun
Pemerintahan Marga.
Limparan
yang berasal dari Basma mungkin terinspirasi dengan daerahnya yang cukup
luas-bersatu. Sehingga memberi saran agar Depati Samsudin juga memperluas
wilayah kekuasaannya. Sepertinya Limparan orang terdidik, mungkin seorang ulama
yang memiliki tugas memperbaiki sosial masyarakat yang sangat tradisional itu.
Organisasi dan Penyatuan
Atas
saran Limparan maka dilakukan musyawarah adat, antara jurai tue Dusun Rengas
Gemuruh dan Depati Samsudin. Ditetapkan Depati Samsudin sebagai pemimpin
tertinggi dan menjadi Depati pemimpin marga setelah marga terbentuk. Seseorang
bergelar Bujang Piamang diangkat sebagai panglima, yang membawahi
hulubalang-hulubalang. Pasukan terdiri dari pasukan sukarela yang berasal dari
tumang-tumang (klan) dalam desa mereka.
Hasil
musyawarah: mendirikan tempat pemerintahan marga, mengajak kelompok-kelompok
kecil atau talang-rompok sekitar pindah membentuk pemukiman dusun. Membentuk
menjadi satu marga (kepuyangan), Depati Samsudin sebagai Depati pemimpin marga,
dan mengamankan lalu lintas perairan Sungai Musi.
Ilmu Tombok
Ilmu
tombok adalah ilmu cara-cara. Misalnya kalau mencari benda hilang dengan
memukul air liur di tangan. Agar ikan asin asinnya berkurang direndam dengan
air garam. Kalau mau membangun rumah ukuran di sukat. Sukat hitungan dengan
omongan tertentu sesuai harapan, dan lain-lain.
Begitu
juga dalam mencari lokasi pembangunan pusat pemerintahan marga. Depati
Samsudin, Limparan dan beberapa pengawal menyusuri hutan di Daerah Kinyau.
Limparan membawa ayam beruge jantan. Mendatangi tempat tertentu dan meletakkan
ayam. Kalau ayam beruge berkokok maka tempat itulah yang akan dijadikan
pemukiman baru.
Setelah
lama mencari sampai masuk sungai Rawas anak sungai Musih ayam yang diletakkan
tidak berkokok sampai mereka kembali lagi, Di seberang lokasi pemukiman mereka
Limparan kembali meletakkan ayam beruge. Ayam beruge akhirnya terbang dan
berkokok. Maka tempat itulah yang mereka jadikan lokasi pembangunan pemukiman
baru.
Depati Samsudin memerintahkan penduduk pindah ke seberang dan dinamakan Talang Rengas. Sampai sekarang posisi Talang Rengas masih ada masuk administrasi Desa Ngulak. Istilah kampung memang menghilangkan istilah talang di kebanyakan desa-desa di Sumatera Selatan di zaman sekarang. Hal ini perlu di perhatikan agar tidak menghilangkan ciri khas daerah. (Bersambung)
Baca kelanjutannya klik di sini. Bagian II. Bagian III.
























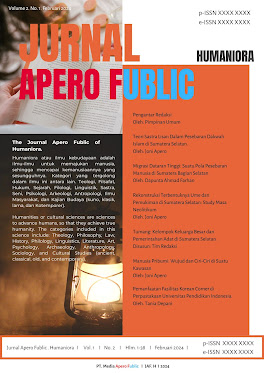

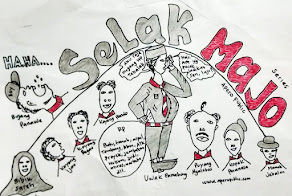






.jpg)




.jpeg)





.jpg)





Izin bertanya,buku H.Yusman Haris mengenai sanga desa dri masa ke masa nyarinya dmna yah?
ReplyDelete